SASTRA BIRU: MENEROKA ESTETIKA SASTRA MARITIM KITA
aku cinta pada laut, laut cinta padaku dan cinta kami seperti kata-
kata
dan hati yang mengucapkannya.
[Sajak “Laut”, Abdul Hadi W.M.]
Laut adalah wilayah utama negara Indonesia dengan dua pertiga bagiannya berupa lautan yang mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Lautan Indonesia ditaburi pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.504 pulau yang menjadikan negara ini sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Profesor Adrian Lapian mengingatkan bahwa julukan archipelagic state bagi Indonesia tidaklah diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Dengan mencermati aspek bahasanya, archipelago berasal dari bahasa Yunani yaitu arch yang berarti utama dan pelages berarti laut. Profesor Lapian menyimpulkan bahwa laut adalah utama, maka archipelagic state bermakna negara laut yang ditaburi pulau-pulau. Melihat berbagai fakta tersebut, narasi besar Indonesia adalah narasi tentang laut.
Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari budaya laut. Laut adalah sarana transportasi, potensi ekonomi, wahana wisata bahari, dan penyeimbang ekosistem alam. Ikan telah menjadi makanan kita sehari-hari. Garam adalah bumbu yang tak pernah luput dari masakan kita. Pantai adalah salah satu tujuan wisata utama. Masyarakat pesisir adalah kita dan masyarakat di sekitar kita. Laut sebagai ruang budaya ini telah jauh merasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
Laut sebagai karakter geografis khas negeri kepulauan ini juga menjadi ruang ide bagi para pengarang dalam menciptakan karya-karyanya. Novelis, cerpenis, dan penyair menjadikan laut sebagai obor kreatif bagi imajinasi-imajinasinya. Dalam khazanah puisi, laut bermetamorfosis menjadi tema, metafora, simbol dan citra. Dalam khazanah prosa, laut menjadi ruang yang dinamis yang merekam pergulatan budaya, antara asing-asli, global-lokal, tradisional-modern dan bersatu-bercerai. Sastra yang menarasikan laut ini dapat disebut sebagai sastra maritim atau sastra biru.
Esai ini adalah upaya untuk menawarkan cara pandang baru dalam melihat karya sastra kita, yaitu melalui kaca mata kritik sastra maritim atau blue studies. Keberlimpahan karya sastra indonesia, baik itu novel, cerita pendek atau puisi, yang menarasikan tentang laut akan menghasilkan pembacaan yang kaya dan memiliki sudut pandang berbeda jika kita bertitiktolak dari laut. Kritik sastra maritim adalah usaha untuk mengarahkan pandangan kita ke laut.
Sastra Maritim dan Estetika Biru
Kajian sastra maritim atau blue studies menandai kemunculannya pada dekade awal abad ke 21 ini. Dengan menjadikan laut sebagai titik tolak, kajian ini tentu menantang kebiasaan berpikir (habits of thought) yang telah mapan. Kajian maritim menitikberatkan laut tidak sebagai objek tetapi subjek yang berperan aktif. Dengan laut sebagai pijakan, beberapa kritikus sastra melihat kembali sastra inggris dan sastra amerika pada periode modern awal yang memberikan perspektif baru tentang relasi ekologis dan koneksi multikultural antar bangsa. Karya-karya di antaranya adalah Maritime Fiction: Sailors and the Sea in British and American Novels 1719-19-17 (Peck, 2000), Fictions of the Sea: Critical Perspective on the Ocean in English Literature and Culture (Bernhard & Mackenthun, 2002), “Toward a Blue Cultural Studies: The Sea, Maritim Culture and Early Modern English Literature” (Mentz, 2009).
Kajian interdisipliner sastra dan dunia maritim menarik tidak hanya terkait dengan apresiasi terhadap representasi laut dan narasi kultural pembentuknya, tetapi juga laut sebagai unsur estetika karya sastra. Estetika ini dapat disebut sebagai estetika biru, merujuk kepada warna laut yang biru. Kajian sastra maritim diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memandang karya sastra seperti pendekatan-pendekatan baru dalam wacana modern seperti kiritik sastra poskolonial, kritik sastra ekologis (ecocriticism) dan kritik sastra kuliner (gastrocriticism).
Kritik sastra biru dalam konteks Indonesia menjadi relevan hari-hari ini dilihat dari dua hal. Pertama, kritik sastra maritim sebagai bagian dari gerakan arus balik kebudayaan untuk melihat kembali laut sebagai ruang sosial, kultural dan historis masyarakat Indonesia. Hilmar Farid dalam Pidato Kebudayaannya pada tahun 2014 berjudul “Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik” menekankan akan signifikansi laut dan pelabuhan dalam bangunan sejarah Indonesia. Ia juga mewanti-wanti agar kita sepenuhnya sadar bahwa secara historis laut adalah bagian tak terpisahkan dari ruang sosial dan kultural kita. Gerak budaya menghadap laut ini salah satunya dimulai oleh Adrian B. Lapian dengan disertasi yang berjudul “Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Selawesi Abad XIX” yang mempelopori sejarah maritim dalam melihat historiografi indonesia. Undang-undang Kelautan nomor 32 tahun 2014 juga telah disahkan meskipun sangat terlambat dan berjarak 69 tahun dari kemerdekaan negara maritim ini. Maka, kritik sastra biru dapat menjadi salah satu lokomotif untuk membalik gerak budaya ‘memunggungi laut’ menjadi gerak budaya ‘laut sebagai halaman depan rumah kita’.
Kedua, kritik sastra maritim atau blue studies sebagai kajian kritis dalam melihat kerusakan laut akibat perbuatan manusia seperti pemanasan global (global warming), sampah plastik, perusakan biota laut, illegal fishing dan sebagainya. Perubahan iklim akibat pemanasan global telah mencairkan es kutub dan menaikkan permukaan air laut. Hal ini memiliki dampak nyata terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat kepulauan seperti banjir laut dan erosi pantai yang merusak mangrove, tambak ikan, udang dan ladang garam. Indonesia dengan panjang garis pantai 95.000 kilometer tentu tak lepas dari dampak alam ini. Ketika laut terancam rusak, maka kerjasama berbagai bidang keilmuan sangatlah dibutuhkan, termasuk sastra. Sastra memiliki kekuatan yang menawarkan cara pandang berbeda dari disiplin ilmu lain, yaitu merasuki relung-relung hati manusia. Maka, kritik sastra biru menjadi pelantang dalam upaya pelestarian laut dan ekosistemnya.
Dua titik pijak tersebut dapat menjadi acuan dalam mengungkap kandungan dan makna sastra maritim dari berbagai segi. Pertama, sastra maritim yang mengisahkan laut dari diri laut itu sendiri dan benda-benda mati di sekitarnya seperti pantai, flora dan fauna di dasar laut, kapal, sampan, pelabuhan dan lain sebagainya. Karya sastra semacam ini berfokus hal-hal di luar antroposen dan cenderung memandang laut yang statis dan membeku (freezing), yaitu keindahan laut yang digambarkan sehingga narasinya mendayu-dayu, penuh kekaguman dan sarat akan eksotisme. Keindahan laut dipandang sebagai sesuatu yang terberi (given), dan mengabaikan aspek-aspek perbuatan manusia dan dinamika alam.
Kedua, terdapat pula sastra maritim yang mengisahkan laut sebagai ruang budaya bagi kehidupan manusia. Karya-karya semacam ini mencatat aktivitas-aktivitas kebudayaan seperti upacara petik laut, penciptaan kapal laut dan lain sebagainya. Karya-karya sastra juga bercerita tentang pergeseran kebudayaan seperti anak pesisir yang tidak lagi pandai melaut, kemunculan teknologi yang mengganti cara menangkap ikan, problematika masyarakar pesisir akibat kerusakan laut, konflik antar nelayan dan laut sebagai wahana rekreasi belaka. Laut sebagai ruang budaya tidak bersifat statis tetapi dinamis dan terus bergerak.
Khazanah Sastra Maritim Indonesia
Dari khazanah puisi, laut menjelma menjadi beberapa judul buku puisi dari beberapa penyair seperti Sutan Takdir Alisjahbana dengan dengan buku puisi Lagu Pemacu Ombak[1] dan Abdul Hadi W.M. dengan buku puisi Laut Belum Pasang[2]. Banyak pula ditemukan beberapa judul puisi yang berhubungan dengan laut yang ditulis oleh penyair-penyair negeri ini. Contohnya adalah Chairil Anwar dengan puisi “Kabar dari Laut”[3] (1946), Subagio Sastrowardoyo dengan puisi “Soneta Laut” (1989)[4], Sitor Situmorang menulis puisi “Pelaut 1” dan Pelaut 2”[5], Rendra menulis sajak “Lautan”[6] dan Mardi Luhung mengarang “Penganten Pesisir” (1993). [7]
Untuk keperluan tulisan ini, penulis akan mengajukan salah satu penyair yang kerap menggunakan laut dalam puisi-puisinya, yaitu D. Zawawi Imron dari Madura. Beberapa judul buku puisinya bertolak dari laut, seperti Madura, Akulah Laut-Mu (1978), Berlayar di Pulau Badik (1994), Laut-Mu tak Habis Gelombang (1995), Bantalku Ombak Selimutku Angin (1996), Kelenjar Laut (2007), Jalan Hati Jalan Samudra (2010). Mari kita lihat salah satu puisi Zawawi Imron berikut ini:
Tamsil Laut saat Gulita
Di laut yang gulita hatimu berendam
bersama daun-daun lokan
karang yang amis dibelai ombak
mengisyaratkan
uap air yang meninggalkan garam
aku tak tahu
apa doamu yang membumbung
atau langit yang merendah
karena bunga tetap setia pada kelopak?
Dalam zikirmu terumbu pun diam
Seperti mendengar rahasia yang menyejukkan
Saat mata kaubuka
Laut kembali biru dan langit kembali tinggi
Sebuah pencalang sedang melompati cakrawala
[Laut-Mu Tak Habis Gelombang, hlm. 14]
Dari pembacaan atas puisi tersebut, nuansa laut nampak begitu dekat, tak berjarak, dan sangat akrab. Keakraban ini membuat kita terbuai dan terpesona dengan keindahan laut. Dengan lihai, Zawawi mengolah berbagai sarana penciptaan puisi seperti metafora, personifikasi dan citraan (imagery) dalam mendeskripsikan laut. Dalam pembacaan yang lebih beragam terhadap beberapa puisi-puisinya, laut dalam imajinasi Zawawi Imron sangatlah menarik dilihat dari empat hal. Pertama, laut adalah simbol dan lambang yang menyimpan gagasan penyair. Laut sebagai tidak hanya sebagai latar, tetapi juga ide dan pernyataan ekspresi penyair. Kedua, puisi-puisinya cenderung surealis yang memperbaurkan realitas formal dan realitas imajiner. Ketiga, puisi-puisinya berasal dari simbol dan lambang lokal Madura yang kemudian dihancurkan makna konvensionalnya dan diganti makna baru. Keempat, dikisi-diksi tentang laut digabungkan dengan kata-kata religius.
Pembacaan yang lebih mendalam dan intensif masih diperlukan untuk menemukan makna laut dalam imajinasi Zawawi Imron dan juga penyair-penyair lainnya. Tentu, sesuatu yang menarik akan ditemukan jika melihat bagaimana pemaknaan laut dengan membaca laut dari satu penyair ke penyair lain, dari satu puisi ke puisi lain, dari satu masa ke masa lain dan dari satu generasi ke generasi lainnya.
Dari khazanah prosa, banyak pula ditemukan karya-karya yang mengangkat kehidupan seputar laut. Tentu, karya yang paling banyak dibicarakan sebagai sastra maritim adalah Arus Balik karya Pramoedya Ananta Toer. Sebagaimana karya-karyanya yang lain, Pram dalam novel ini bergulat dengan isu-isu besar seperti kebangsaan, kekuasaan, kemanusiaan terutama berhubungan dengan “bagaimana menjadi indonesia”.
Pram berkisah bahwa sejak dahulu negara maritim ini adalah negara dengan pergaulan antarbangsa yang luas yaitu pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka, Tuban, Banten, Makassar, Ternate, Tidore menjadi jujukan pedagang-pedagang dari Arab, Eropa dan India. Namun, lambat laun, pelabuhan-pelabuhan kerajaan tersebut jatuh ke tangan VOC karena ketidakmampuan mengorganisir diri dalam persatuan dalam melawan penjajah. Kejatuhan ini disebabkan oleh setiap kerajaan yang ingin menang sendiri, bersikap feodal dan tidak berpikir jauh. Hanya Adipati Unus, putra Raden Fatah Demak, yang berusaha merebut Malaka dengan mempersatukan berbagai kerajaan maritim. Namun, gayung tidak bersambut karena pasukan gabungan dari Tuban dan Banten memperlambat kedatangan demi misi mereka sendiri.
Dalam novel Arus Balik, narasinya berasal dari seorang tokoh bernama Wiranggaleng, seorang pemuda desa sekaligus juara gulat yang terjerembab ke dalam intrik-intrik kekuasan karena diangkat sebagai pemimpin militer oleh Adipati Wilwatikta di kota pelabuhan Tuban pada abad ke 15. Dalam melihat berbagai perebutan kekuasaan ini, Wiranggaleng berpendapat bahwa kunci persatuan adalah kekuasaan atas laut. Nusantara akan hancur jikalau penguasa dan raja mengabaikan kekuatan di atas laut. Ia berkata:
“Sekarang orang tak mampu lagi membuat kapal besar. Kapal kita makin lama makin kecil seperti kerajaannya. Karena, ya, kapal besar hanya bisa dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya, dari utara sekarang ke selatan, karena Atas Angin lebih unggul, membawa segala-galanya ke Jawa, termasuk penghancuran, penindasan dan penipuan. Makin lama kapal-kapal kita akan semakin kecil untuk kemudian tidak mempunyai sama sekali.”
[“Arus Balik”, Pramoedya Ananta Toer]
Kehancuran kerajaan maritim karena perebutan kekuasaan kembali dimanfaatkan oleh VOC juga menjadi narasi prosa, yaitu dalam novel Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y.B. Mangunwijaya. Kali ini adalah tentang perseteruan kerajaan Ternate dan Tidore yang menguntungkan orang-orang VOC.
Tetapi sekarang orang-orang Holan lebih buas lagi. Dan orang-orang Ternate sendiri? Satu-satunya nafsu mereka cuma bagaimana menghambakan orang Tidore. Setali tiga uang. Kalau orang-orang di sebelah barat halmahera sana, entah kulit ulin entah kulit udang, maunya cuma merampok orang-orang pantai timur, mengapa tidak dibalas setimpal (Mangunwijaya, 2015:215).
Dalam novel ini, kita melihat kekayaan budaya maritim kita seperti tradisi masyarakat pesisir Suku Tobelo di Maluku dalam melangsungkan kehidupannya seperti tradisi menangkap ikan, membuat kapal, pesta dopa-dopa, tradisi perkawinan dan tradisi perkawinan.
Kedua novel ini membuktikan bahwa narasi besar bangsa ini adalah narasi maritim tentang laut. Kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kita ditopang oleh pergerakan kehidupan di sekitar laut. Namun, seperti yang ditegaskan Hilmar Farid dalam pidato kebudayaannya, kekuasaan VOC atas pelabuhan-pelabuhan maritim adalah awal dari gerak memunggungi laut karena VOC tidak hanya menguasai akses-akses ekonomi, akan tetapi juga memutus rantai pengetahuan dan kebudayaan bangsa akan budaya maritimnya. Novel Arus Balik karya Pramoedya Ananta Toer dan novel Ikan Hiu, Ido, Homa karya Mangunwijaya mendokumentasikan narasi-narasi budaya maritim tersebut dengan memukau. Di tangan dua novelis besar negeri ini, tercatat bahwa kekuasaan dan kebudayaan maritim sangatlah berkaitan erat.
Khazanah cerita pendek sastra kita juga tak luput mengisahkan tentang masyarakat pesisir. Pergolakan pandangan, keterasingan diri, dan pewarisan tradisi maritim mewarnai masyarakat yang tinggal di pinggir laut. Contohnya adalah dalam kumpulan cerpen Karapan Laut karya Mahwi Air Tawar, pengarang dari Madura. Yusri Fajar (2018) mencatat bahwa cerpen-cerpen tersebut mengisahkan dua generasi yang berbeda yang hidup di pesisir laut. Satu generasi mampu berenang dengan baik dan mampu menaklukkan laut. Generasi dengan tokoh Mattasan dan Julantip mewarisi tradisi nenek moyangnya di Madura yang memiliki keahlian melaut. Ini adalah generasi yang tidak terasing dengan lingkungan pesisirnya. Namun, keduanya dipandang rendah oleh teman-teman sekolahnya karena jarang masuk sekolah dan keahlian melaut belum dipandang sebagai bagian dari pendidikan.
Ada pula generasi yang tak mampu berenang dan tak bisa melaut karena sejak kecil dilarang oleh ayahnya untuk pergi ke laut. Karena nelayan dianggap sebagai profesi yang kolot dan tidak beradab. Lebih baik sekolah daripada melaut, katanya. Generasi semacam ini menjadi generasi yang terasing dari kebudayaannya. Mahwi meletakkan kedua generasi ini dalam posisi yang bertolak belakang untuk menjawab sebuah pertanyaan: masih adakah generasi pesisir yang mau melaut di masa depan?
Tradisi melaut juga mendapatkan tantangan di dalam cerpen “Perempuan Rantau” karya Faisal Oddang dalam kumpulan cerpen Sawerigading Datang dari Laut (2019). Cerpen ini bercerita tentang tradisi merantau bagi laki-laki dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.
Di kampungnya, setelah disunat, tidak ada yang boleh berkulit tawar. Kulit laki-laki harus berasa asin, berasa laut. Kelaki-lakian seseorang diukur dari kecakapannya membentang layar menghalau ombak. Yang nyata laki-laki adalah mereka yang mampu mendayung perahu, menyebar jala, dan menyelami laut. Pantang gemetar sebergetar apa pun perahu karena tiupan angin. Dan, akan lebih lelaki jika ia memutuskan merantau, meninggalkan kampung dengan sebentang layar kusut, lalu kembali dengan perahu yang berlayar sutra. Itu pula yang dilakukan Masse, ia merantau meninggalkan janji kepada Sennang dan keluarganya. Tak ada yang tahu ke mana perahunya akan bersandar, angin yang membawanya angin pulalah yang akan mengembalikannya. Begitulah keyakinan para pelaut Bugis. Pun sama dengan keyakinan Masse (Oddang, 2019: 109).
Karena merantau, lelaki Bugis meninggalkan calon isterinya hingga si perempuan menunggu sang kekasih dalam waktu yang lama. Dalam cerpen ini, saking lamanya, Sennang takut menjadi perawan tua. Ia ingin agar segera menikah tanpa lagi menunggu Masse yang tak tahu kapan akan pulang. Akan tetapi Indo (bapak) dan Ambo (ibu) Sennang tidak mengijinkan karena berlawanan dengan adat sirri’ karena terkait dengan harga diri keluarga. Bahwa perempuan harus menunggu calon suaminya yang sedang merantau. Namun, kedua orangtuanya kemudian mengubah pikirannya karena ada lelaki bernama Baso yang mampu membayar uang panai atau mahar lebih tinggi. Adat telah dikalahkan oleh materi.
Maaf, kami berani memahari Sennang dengan sehektar empang. Sepasang perahu. Serta tujuh ekor kerbau. Kami pula yang akan menanggung biaya mulai dari lamaran sampai hari pernikahan (Oddang, 2019: 11)
Cerpen-cerpen ini menunjukkan bahwa melestarikan budaya maritim tidaklah semudah membalikkan tangan. Budaya maritim adalah jalinan tali temali permasalahan yang kompleks. Diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam memilih dan memilah budaya maritim yang hendak kita hadapkan wajah kita.
Pembacaan terhadap berbagai puisi laut dapat menyuntikkan kesadaran akan keindahan lautan nusantara. Membaca puisi-puisi tersebut membawa kita mengimajinasikan laut yang memukau dan menyejukkan hati kita. Di sisi lain, pembacaan terhadap prosa tentang laut membawa kita menelusuri sejarah maritim kita dan mengerti kompleksitas budaya maritim yang dihidupi masyarakat pesisir. Pembacaan terhadap sastra maritim kita melalui kritik dan apresiasi adalah usaha dalam mencintai laut sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa ini. Semoga!
Referensi:
Fajar, Yusri. “Sastra Maritim: Generasi Pesisir dalam Cerpen Mahwi Air Tawar”, Horison, No. 8, Agustus 2015
Farid, Hilmar. “Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik,” Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 2014.
Imron, Zawawi. Laut-Mu tak Habis Gelombang. Yogyakarta: Gama Media. 2000.
Klein, Bernhard and Gesa Mackenthun, eds. Fictions of the Sea: Critical Perspectives on the Ocean in English Literature and Culture. Aldershot: Ashgate Publishing, 2002.
Klein, Bernhard and Gesa Mackenthun, eds. Fictions of the Sea: Critical Perspectives on the Ocean in English Literature and Culture. Aldershot: Ashgate Publishing, 2002.
Mangunwijaya, Y.B. Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa. Jakarta: Kompas. 2015.
Ments, Steven. “Toward a Blue Cultural Studies: The Sea, Maritime Culture and Early Modern English Literature”, Literature Compass 6/5, 2009, p. 997-1013
Oddang, F. Sawerigading Datang dari Laut. Yogyakarta: Diva Press. 2019.
Peck, John. Maritime Fiction: Sailors and the Sea in British and American Novels, 1719–1917. New York: St Martin’s Press, 2000.
Toer, Pramoedya Ananta. Arus Balik. Jakarta: Hasta Mitra, 1995, hlm. 737.
[1] Sutan Takdir Alisjahbana, Lagu Pemacu Ombak (Dian Rakyat, cetakan kedua, 1984)
[2] Abdul Hadi W.M., Laut Belum Pasang (Jakarta: Litera, 1971)
[3] Chairil Anwar, Aku ini Binatang Jalang: Koleksi Sajak 1942-1949 (Jakarta: Gramedia, 1993)
[4] Subagio Sastrowardoyo, Dan Kematian Makin Akrab (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 109.
[5] Sitor Situmorang, Bunga di Atas Batu, (Jakarta: Gramedia, 1989) hlm. 14-15)
[6] W.S. Rendra, Sajak-Sajak Sepatu Tua, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987, 42-43)
[7] Mardi Luhung, Ciuman Bibirku yang Kelabu (Yogyakarta: Akar Indonesia, 2007) 3-4
Esai ini telah terbit di Majalah Suluk Dewan Kesenian Jawa Timur Edisi 19 Tahun 2021 Halaman 17-25
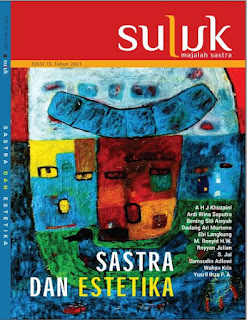

Komentar
Posting Komentar